
Nusantaratv.com-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyesali hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama (mempelai pria beragama Kristen, dan mempelai wanita beragama Islam), dan mengingatkan kembali agar hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan MA sendiri untuk mentaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak mengesahkan pernikahan beda agama, serta fatwa MUI yang menolak pernikahan beda agama (seperti perempuan Muslimah dinikahi oleh pria yang tidak beragama Islam).
Hakim pengadilan negeri seharusnya mengundang dan mendengarkan pendapat MUI sebagai otoritas keagamaan di Indonesia, apabila ada permohonan pengesahan pernikahan apabila salah satu mempelainya beragama Islam. Dalam konteks Indonesia sebagai negata hukum, para hakim harusnya juga mentaati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Apalagi MK sudah berulang kali menolak permohonan uji materi UU Perkawinan untuk membolehkan perkawinan beda agama.
“Para hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat yang juga mengabulkan permohonan perkawinan beda agama itu telah mengabaikan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, yang mengenal adanya hierarki perundangan yang harusnya ditaati. Dengan MK untuk yang kesekian kalinya menolak pengesahan perkawinan beda agama, itu seharusnya menjadi rujukan utama oleh hakim PN, karena menurut UUD NRI 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat, termasuk mengikat para hakim di lingkungan MA,” jelasnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (25/6).
Sebagai informasi, HNW sapaan akrabnya sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut melihat fenomena para hakim PN yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sebelum kasus di PN Jakpus ini, hakim PN Surabaya, PN Yogyakarta, PN Tangerang dan PN Jakarta Selatan juga melakukan hal serupa, padahal itu tak sesuai dengan Konstitusi, Keputusan MK, UU Perkawinan dan Fatwa MUI.
HNW menilai pandangan MUI dan Muhammadiyah di dalam berbagai kesempatan – termasuk dalam persidangan judicial review berkaitan perkawinan beda agama di Mahkamah Konstitusi – telah berulangkali mengungkapkan tidak dibolehkannya perkawinan beda agama berdasarkan aturan agama Islam dan UU Perkawinan. Itu harusnya disimak dan dirujuk oleh para Hakim.
“Ini seharusnya yang menjadi pegangan utama para hakim apabila menghadapi permohonan “pengesahan” perkawinan beda agama dimana salah satu pasangannya beragama Islam,” ujarnya.
“Dan mestinya MA mendisiplinkan para hakimnya untuk melaksanakan ketentuan konstitusi, mentaati keputusan MK, merujuk kepada UU Perkawinan, dengan juga merujuk kepada fatwa MUI. MA perlu menertibkan para hakim di bawah lingkungan kewenangan MA, agar terjadi tertib hukum di negara hukum Indonesia, agar tidak terulang kembali masalah pengabulan permintaan pernikahan beda agama yang meresahkan masyarakat serta mengganggu harmoni sosial di internal umat beragama. Agar tidak terjadi lagi laku hukum yang tidak sesuai dengan norma hukum tertinggi (UUD) dan lembaga hukum dengan otoritas tertinggi (MK), dan ketentuan Agama yang diakui di negara hukum Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, HNW juga menegaskan bahwa UUDNRI 1945 memang mengakui adanya perkawinan tapi perkawinan yang sah, dan tolok ukurnya adalah yang sah menurut ajaran agama. Hal demikian itulah yang sesuai dengan Hak asasi manusia yang dijamin dan diperbolehkan oleh UUD NRI 1945, yakni Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2). Inilah yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menolak berbagai permohonan uji materi UU Perkawinan yang ingin melegalkan perkawinan beda agama.
HNW mengkritik pertimbangan Hakim PN Jakpus yang berdalih menggunakan alasan sosiologis dalam mengabulkan permohonan. Ia menegaskan bahwa Pasal 28B ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan, yang dimaksud perkawinan yang sah adalah yang diatur dalam UU Perkawinan yaitu apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Memang, lanjut HNW, UUD NRI 1945 memungkinkan ketentuan HAM, termasuk Pasal 28B ayat (1) itu dapat dibatasi. Namun, pembatasannya harus merujuk kepada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, bukan dengan alasan yang sumir dan dibuat-buat.
“Alasan pembatasan yang dimaksud oleh UUD terdiri dari beberapa hal, yakni alasan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Jadi, sebenarnya UUD tidak menyebut alasan sosiologis sebagai pertimbangan, sebagaimana yang dilakukan oleh hakim di PN Jakarta Pusat itu. Namun, sekalipun alasan sosiologis itu digunakan, harus tetap sejalan dengan ketentuan UUD antara lain nilai-nilai agama, hal itu secara tegas disebut dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945”tukasnya.
“Oleh karenanya, para hakim termasuk yang di PN Jakarta Pusat, seharusnya merujuk kepada berbagai putusan MK tersebut, di antaranya putusan No. 06/PUU-XII/2014, karena putusan MK oleh UUDNRI 1945 pasal 24C ayat (1) dinyatakan sebagai bersifat final dan mengikat, termasuk dan terutama kepada atau untuk para penegak hukum. Itu semua dipentingkan demi keadilan dan tertib hukum di NKRI yang dinyatakan sebagai negara hukum oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,” tegasnya.
Lebih lanjut, HNW menambahkan agar umat beragama, umat Islam dan lain-lainnya, yang akan menikah, hendaknya memahami hukum agama Islam atau agama lain yang dianutnya terkait dengan perkawinan, juga memahami UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia yang jelas tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama.
“Para orangtua juga mestinya mengingatkan atau mendidik anak-anaknya agar tidak salah memilih calon suami/istrinya, agar pilihannya sesuai dengan ajaran agamanya (Islam atau yang lainnya) dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga bisa menghadirkan masyarakat plural yang toleran dengan taat hukum yang berlaku, sehingga bisa hadirka perkawinan yang menghadirkan prinsip keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dan berkah,” jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang antara lain membidangi urusan keagamaan ini mengkritisi salah satu rujukan yang digunakan oleh hakim di PN adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”
Namun, lanjutnya, hakim-hakim yang memutus perkara tersebut seharusnya tidak hanya melihat pasal itu secara sepotong dan letterlijk, apalagi dengan mengabaikan ketentuan UUD dan putusan MK. Harusnya demi keadilan dan kebenaran, para Hakim selain merujuk kepada UUD dan putusan MK, harusnya para Hakim juga memperhatikan risalah pembahasan RUU Adminduk untuk memahami original intent atau maksud asli ketentuan tersebut.
“Jadi, tidak menghasilkan penetapan yang bisa menghadirkan disharmoni sosial karena juga bertentangan dengan nilai-dan norma agama yang ada di Indonesia khususnya Islam, yang tidak membolehkan pernikahan beda agama seperti wanita Muslimah dengan pria yang berbeda agama,” tuturnya.
HNW mengingatkan bahkan bila UU Adminduk dirujuk, maka beberapa poin penting di Risalah Pembahasan RUU Adminduk tersebut menegaskan bahwa UU Adminduk itu hanya bersifat “pencatatan” perkawinan, BUKAN “pengesahan”perkawinan. Oleh karenanya, ketika ada pemberitaan bahwa hakim telah mengesahkan perkawinan beda agama di sejumlah media, maka telah terjadi kerancuan di masyarakat, dan ketidaksesuaian dengan norma hukum yang lain.
“Yang mungkin bisa itu hanyalah penetapan pencatatan perkawinan bukan pengesahan itupun diluar dari mempelai yang salahsatunya beragama Islam. Karena sahnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan,” ujarnya.
Kedua, lanjut HNW, Risalah Pembahasan RUU Adminduk secara jelas dan tegas menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tetap menjadi rujukan utama terkait dengan perkawinan, dimana salah satu ketentuannya menyebut dengan tegas dan jelas bahwa ‘Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”
“Lalu, bagaimana para hakim itu bisa memahami hukum masing-masing agama para pasangan perkawinan, apabila mereka tidak mendengarkan pendapat pemuka agama atau lembaga kegamaan yang memiliki otoritas, dan dalam konteks keislaman adalah MUI. Apalagi MUI telah berulang kali dengan tegas menyatakan bahwa Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama adalah tidak sah,” ujarnya.
HNW mengatakan sejak awal memang ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk memang sudah diwanti-wanti oleh salah satu pembahasnya, yakni Anggota FPKS DPR RI yang sekarang sudah wafat; Suryama Majana Sastra, untuk tidak menabrak aturan dalam UU Perkawinan. Di dalam Risalah Pembahasan RUU Adminduk, Suryama tercatat menyampaikan:
‘Kalau kita tidak hati-hati di sini misalnya, ini seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, pengadilan bisa menjadi satu lembaga yang mensahkan atau melegitimasi, dan ini bisa jadi nanti kontradiksi dengan apa yang sudah diatur, oleh UU Perkawinan. Saya kira marilah kita menelaah masalah ini secara tenang, substansial, dan melihat relasinya dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan perkawinan.’
HNW mengatakan apabila para hakim membaca dan mentaati RIsalah Pembahasan RUU Adminduk itu, maka akan dapat dihadirkan komitmen menegakkan dan melaksanakan aturan hukum yang disepakati di Indonesia, dengan UUD, Keputusan MK, UU sesuai hirarkinya yang akan menghadirkan masyarakat taat hukum dan harmoni sosial melalui prosesi Perkawinan yang sah.
”Oleh karenanya para hakim seharusnya tidak hanya melihat penjelasan secara tekstual dan sepotong, tetapi juga merujuk pada penafsiran originial intent, agar memahami teks UU secara utuh. Dan terutama para hakim juga harusnya merujuk kepada ketentuan UUDNRI 1945 dan Putusan MK yang sudah menolak judicial review untuk membolehkan perkawinan beda agama. Dengan demikian MA dapat mendisiplinkan para hakim di bawah kewenangannya, agar dapat mengkoreksi keputusan yang tidak sesuai UUD, seperti keputusan yang mengabulkan pernikahan beda agama, dan tidak lagi membuat keputusan yang tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku yaitu UUDNRI 1945. Agar dengan demikian akan terjagalah harmoni sosial ditengah masyarakat plural agama, bahkan para hakim bisa menjadi contoh yang baik dalam sikap taat hukum dan konstitusi, dan menjadi pembelajaran yang baik bagi rakyat, agar keadilan dan kebenaran tetap bisa ditegakkan di negara hukum Indonesia,” pungkasnya.







 Sahabat
Sahabat Ntvnews
Ntvnews Teknospace
Teknospace HealthPedia
HealthPedia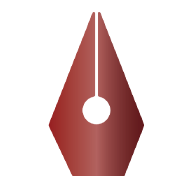 Jurnalmu
Jurnalmu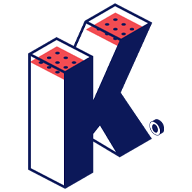 Kamutau
Kamutau Okedeh
Okedeh